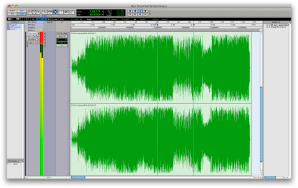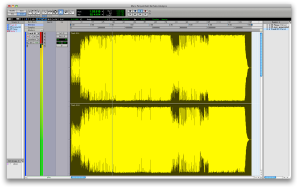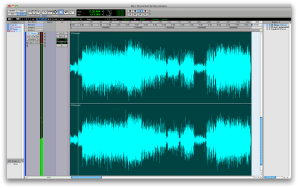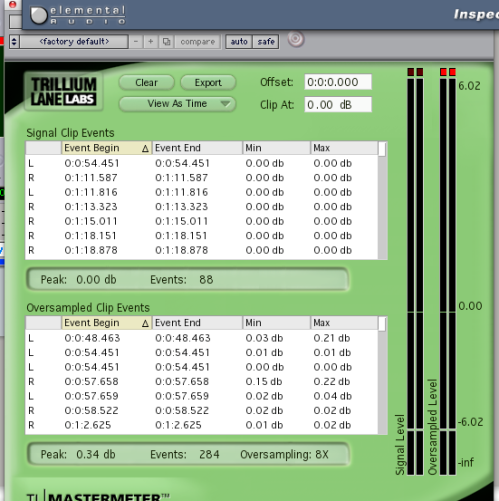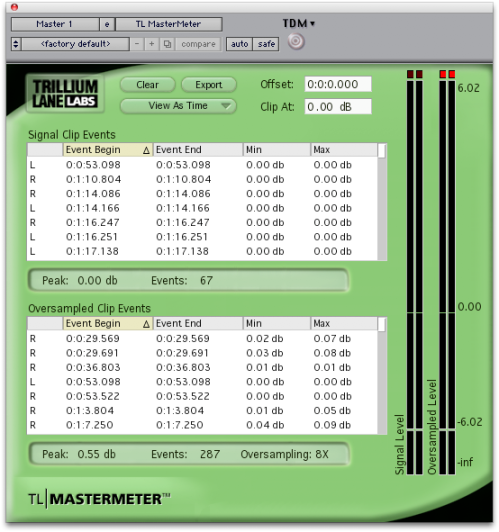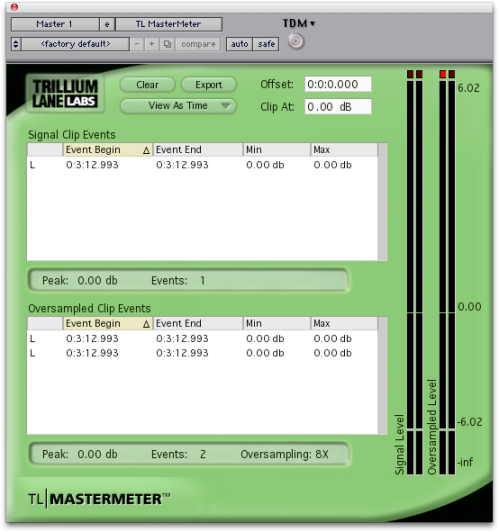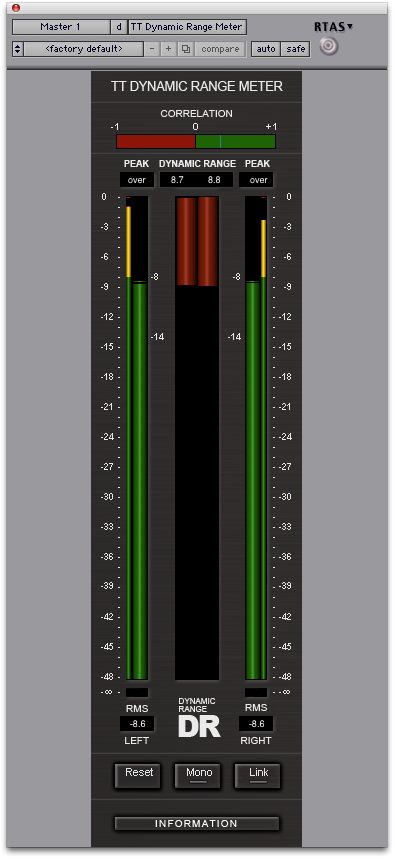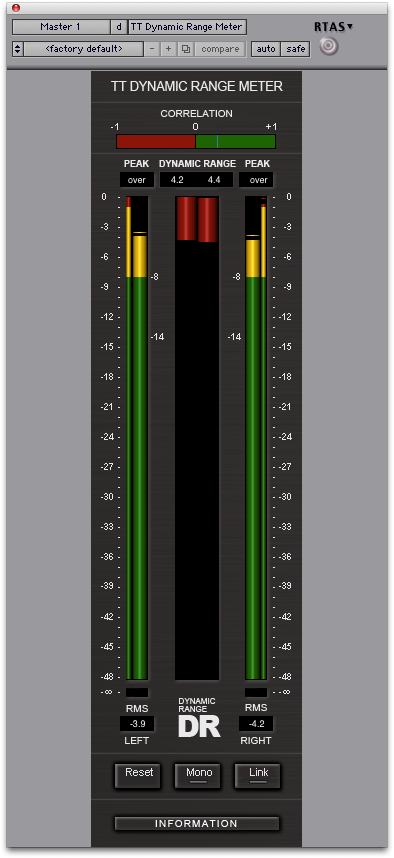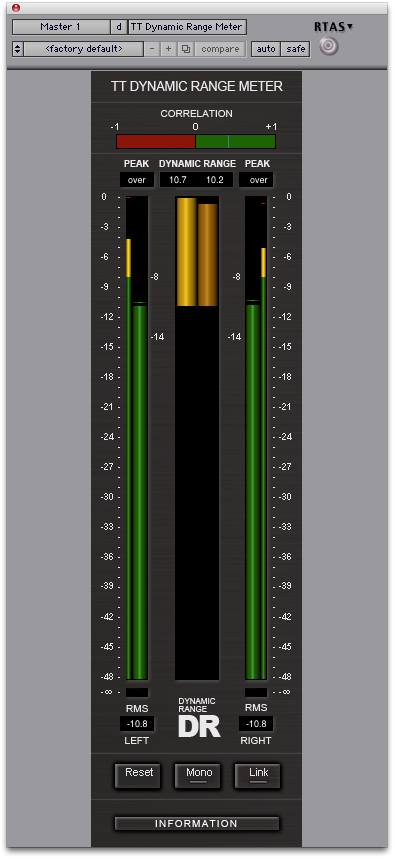Saturday, 19 December 2009 00:41
Oleh Idhar Resmadi, penulis freelance, mahasiswa jurnalistik Universitas Padjadjaran
Menulis album-album terbaik lokal tahun 2009 terhitung gampang-gampang susah. Gampangnya, di tengah industri musik Indonesia yang kian menukik baik secara kualitas maupun kuantitas, relatif mudah untuk memetakan album-album mana saja yang layak menjadi mutiara di laut hitam. Di tengah keseragaman musik melayu, nada-nada pop kreatif tapi tidak kreatif karena bejibunnya keseragaman bermusik, dan tema-tema cinta memuakkan, masih mudah rasanya menemukan band-band yang berani mendobrak perilaku dan selera industri.
Di dunia indie pun, banyak band-band indie yang terjebak menjadi epigon dari pengaruhnya. Dan susahnya, tak ada album yang benar-benar fenomenal di tahun 2009 ini. Tak ada album yang jadi cetak biru semisal 4 Through The Sap milik Pas Band. Kecuali apabila analisis-analisis dibuat subjektif. Ada beberapa album yang menjady hype di tahun 2009, semisal Kamar Gelap (Efek Rumah Kaca), In Medio (Anda), maupun Risky Summerbee and the Honeythief, namun mereka dirilis di penghujung tahun 2008. Alhasil, nikmati saja lima album lokal terbaik tahun 2009 berikut ini:1. Tika and the Dissidents - The Headless Songstrees (Head Records)
 Empat tahun yang lalu kemunculan Tika dianggap mendobrak beberapa hal. Pertama, pada medio tahun 2000-an gampang terlihat fenomena menjamurnya grup musik atau band yang beredar di kalangan para pemusik independen. Tiba-tiba muncul Tika dengan konsep solois perempuan yang membawa warna musik trip hop, noir, dan jazz di tengah gegap gempitanya tren musik emo, garage rock, atau nu-retro di Indonesia pada masa itu.
Empat tahun yang lalu kemunculan Tika dianggap mendobrak beberapa hal. Pertama, pada medio tahun 2000-an gampang terlihat fenomena menjamurnya grup musik atau band yang beredar di kalangan para pemusik independen. Tiba-tiba muncul Tika dengan konsep solois perempuan yang membawa warna musik trip hop, noir, dan jazz di tengah gegap gempitanya tren musik emo, garage rock, atau nu-retro di Indonesia pada masa itu. Kedua, Tika telah mendobrak istilah “Diva” di Indonesia. Yang pasti, ia telah membongkar istilah klise Diva di Indonesia yang seolah terpatri pada Krisdayanti, Titi DJ, atau Ruth Sahanaya dengan konsep glamour bak model iklan sabun dengan kredo lebih ramping, lebih putih, dan berambut lebih lurus. Lewat debut albumnya Frozen Love Songs, para kritikus musik negeri ini mencap Tika sebagai biduanita berbahaya di Indonesia karena memiliki warna musik yang terhitung cutting-edge dan memiliki sikap antitesis dengan kredo diva tersebut.
Pasca-debut album Frozen Love Songs, Tika bisa dikatakan vakum. Kecuali, ia sempat merilis versi kemasan ulangnya dengan nama Defrosted Love Songs pada tahun 2006. Setelah itu Tika seperti daun tertiup angin yang tak ada ujung kabar beritanya.
Tahun 2009, Tika datang lagi. Kali ini ia tampil berbeda dibanding empat tahun lalu. Ia kini tak hadir sendirian tapi ditemani band atau grup musik yang dinamakannya “The Dissidents” yang terdiri dari sejumlah musisi berbakat seperti Susan Agiwitanto, Okky Rahman Oktavian, dan Luky Annash. Warna musik yang mereka usung tidaklah semuram pada album awalnya. Tampaknya penambahan The Dissidents menambah warna baru pada musikalitas Tika. Warna trip-hop murung boleh menjadi minimal, lalu warna musik eklektik fusi dari rock, blues, hingga tango dan waltz terasa lebih mendominasi.
Soal lirik, album The Headless Songstrees tak hanya dipenuhi perasaan Tika yang galau seperti pada albumnya terdahulu. Kali ini ia lebih mulai berani menyuarakan pendapatnya yang tanpa tedeng aling-aling, mengurai borok budaya popular mulai dari televisi, industri musik, hingga diskriminasi sosial. Dengan mengurai tema-tema kritis dan sarkastis, saya hanya bisa tersenyum ketika dalam halaman websitenya Tika menulis para teroris internet mengecamnya terlalu ‘gemerlap’ untuk jadi kiri.
“Kiri” gaya Tika pun sangat terlihat jelas pada lagu berwarna musik mariachi berjudul ‘Polpot”, yang sempat membuat saya terjebak berpikir bahwa lirik ini bercerita tentang pembantai Khmer Merah di Kamboja. Nyatanya, lirik ini bercerita tentang pembantaian intelektual oleh televisi. Atau simak lagu “Clausmophobia” yang bercerita soal persepsi masyarakat terhadap kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Trans-seksual), atau simak juga lagu “Mayday” yang bercerita soal buruh. Hebatnya, lagu ini juga dijadikan soundtrack sebuah organisasi buruh di Amerika.
Kredit Tika sebagai seniman ber-attitude bukan tanpa alasan. Tika dikenal sebagai aktivis gender dan penganut paham DIY (Do It Yourself). Sikap DIY terlihat pada kemasan album The Headless Songstrees di mana Tika merajut dan mendesain sendiri kemasan kain dan patch yang menjadi keunikan dari album ini, dan menjadi daya tarik orang untuk membeli atau sekedar mengaguminya.
2. The S.I.G.I.T.- Hertz Dyslexia E.P. (FFWD Records)
 Tren musik garage revival second wave yang muncul pada awal tahun 2000-an memang memberikan pengaruh besar terhadap proses kreatif band-band Indonesia. Ketika itu masuk pengaruh-pengaruh musikal semacam The Strokes, The White Stripes, Kings of Leon, The Libertines, Jet, dan sebangsanya. Sebagai negara dunia ketiga, sebagai efek dari “korban” berseliwerannya band-band garage revival nongkrong di MTV dan majalah musik macam Rolling Stone, Spin, dan NME maka efek dari pengaruh tersebut menimbulkan zat konsumsi yang secara tak sadar mempengaruhi ekspresi. Maka, beramai-ramailah band Indonesia mendompleng tren tersebut. Misal saja, The S.I.G.I.T. , Speaker 1st (Bandung), dan The Brandals (Jakarta).
Tren musik garage revival second wave yang muncul pada awal tahun 2000-an memang memberikan pengaruh besar terhadap proses kreatif band-band Indonesia. Ketika itu masuk pengaruh-pengaruh musikal semacam The Strokes, The White Stripes, Kings of Leon, The Libertines, Jet, dan sebangsanya. Sebagai negara dunia ketiga, sebagai efek dari “korban” berseliwerannya band-band garage revival nongkrong di MTV dan majalah musik macam Rolling Stone, Spin, dan NME maka efek dari pengaruh tersebut menimbulkan zat konsumsi yang secara tak sadar mempengaruhi ekspresi. Maka, beramai-ramailah band Indonesia mendompleng tren tersebut. Misal saja, The S.I.G.I.T. , Speaker 1st (Bandung), dan The Brandals (Jakarta). Pada tahun 1980-an, lahir band-band sepertiThe Miracle Workers, The Pandoras, Spacemen 3, dan The Brian Jonestown Massacre yang menyuarakan “The Garage Revival Scene”. Band-band ini lahir dari tangan Almarhum Greg Shaw yang memang dikenal sebagai peletak apa yang kita sebut garage music. Ketika pada tahun 1980-an ia memunculkan band-band itu, Greg Shaw tak menyangkal bahwa sound music rock n roll tetap akan hidup di era postmodernisme sekarang ini. Greg Shaw pernah berujar bahwa musik garage akan selalu hidup ketika band-band pasca-revivalist garage ini tetap menyuarakan bisingnya rock n roll era 1960-an macam Led Zeppelin dan The Rolling Stones.
Saya kira pengaruh itu terasa pada album perdana The S.I.G.I.T. , Visible Idea of Perfection. Dalam album itu masih terselip kombinasi antara progenitor rock n roll macam Led Zeppelin dengan sound garage revivalist seperti pada Jet atau The Libertines. Potensi The S.I.G.I.T. sebagai salah satu band rock n roll paling ‘hot’ di Indonesia mulai terlihat ketika beberapa single di album itu berhasil memancing kesuksesan mereka hingga layak tur di negara kangguru dan menyambangi Festival SXSW di Texas pada awal tahun ini.
Bara api yang dikobarkan The S.I.G.I.T. tak padam di album pertama. Bisa dibilang The S.I.G.I.T. justru mengobarkannya lagi lebih besar lewat Hertz Dyslexia yang dirilis pada pertengahan tahun 2009. Album ini muncul di tengah “terjebaknya” band-band garage atau rock n rock lokal seangkatan The S.I.G.I.T. pada dualisme menjadi Led Zeppelin atau The Strokes. Band-band seangkatan mereka terdengar klise dan sami mawon pada tiap album, seperti The Brandals, Jack N Fourmen, atau Speaker 1st.
Sebenarnya, Hertz Dyslexia adalah mini-album The S.I.G.I.T. yang bisa jadi mencerminkan kualitas dan progresi musikal kuartet asal Bandung ini. Ketika band-band garage seangkatan mereka “terjebak”, mereka justru dengan berani bereksperimen dan mendekonstruksi definisi garage music itu sendiri. Di album ini, The S.I.G.I.T. seolah mengenyahkan diri dari pakem-pakem apapun. Ia terlepas dari band garage atau band rock n roll.
Hampir tiap lagu dari tujuh lagu dalam album ini mencerminkan progresi itu. Mulai dari berbau rock stoner pada single “Money Making” dan “The Party”, hingga memasukan elemen seruling bernada psikadelik pada lagu “Bhang”, sampai lagu yang benar-benar dekonstruktif dengan memasukan elemen ambience dan vokal lo-fi pada lagu “Midnight Mosque Song”.
Alhasil, Hertz Dyslexia yang menjadi titik pijak yang menunjukkan bahwa musikalitas The S.I.G.I.T. tak pernah berhenti pada satu titik. Dan bahwa mereka tidak ingin terjebak pada nuansa genre yang tipikal dan membosankan seperti yang terjadi pada band-band seangkatan mereka tadi. Apalah itu namanya garage revival, rock n roll, atau hard rock, The S.I.G.IT. telah menghancurkannya pada diri mereka sendiri.
3. Melancholic Bitch, Balada Joni dan Susi (Dialectic Recordings)
 Salah satu alasan penting kenapa menempatkan Balada Joni dan Susi sebagai salah satu rilisan terbaik di tahun 2009 ini adalah karena keberanian Melancholic Bitch untuk merilis sebuah konsep album. Dewasa ini jarang terdengar sebuah band lokal (indie maupun major) merilis sebuah konsep album di tengah hiruk pikuk kaki industri musik yang bertumpu pada ring back tone (RBT) dan single.
Salah satu alasan penting kenapa menempatkan Balada Joni dan Susi sebagai salah satu rilisan terbaik di tahun 2009 ini adalah karena keberanian Melancholic Bitch untuk merilis sebuah konsep album. Dewasa ini jarang terdengar sebuah band lokal (indie maupun major) merilis sebuah konsep album di tengah hiruk pikuk kaki industri musik yang bertumpu pada ring back tone (RBT) dan single. Alasan itu menempatkan Melancholic Bitch sebagai sebuah band lokal yang layak diperhitungkan. Saya berani bertaruh bahwa Melancholic Bitch adalah band keren yang terlupakan. Pasca dirilisnya debut album Anamnesis pada tahun 2005, band ini seperti menghilang ditelan bumi. Mereka bukan tipikal sebuah band yang instant termasuk memanfaatkan hype internet untuk meraih citra dan popularitas. Sehari sebelum menulis review ini saja, saya melihat halaman Myspace mereka yang masih bertampilan standar dengan jumlah kawan yang minim. Maka taruhan saya dipenuhi dengan spekulasi bahwa Melancholic Bitch adalah sekumpulan seniman yang punya integritas terhadap karya, dan karya itu tak boleh instant, tak boleh gampangan, tapi harus komprehensif, dan tentunya, artistik.
Besar dan berkembang dalam lingkup komunitas seni menjadi alasan yang mencerminkan sikap dan ideologi band asal Kota Gudeg ini. Band ini berangkat dari komunitas seni Kua Etnika, komunitas Teater Garasi, dan komunitas forum musik Fisipol Universitas Gajah Mada. Dari latar belakang kesenimanan mereka, maka Balada Joni dan Susi adalah pergulatan kreativitas, intelektual, dan predikat kesenimanan para personil Melancholic Bitch selama empat tahun.
Dalam sebuah wawancara dengan Jakarta Post, vokalis dan penulis lirik Ugoran Prasad berkomentar soal konsep Balada Joni dan Susi: “"For me, this is a story about a couple who are always trying to pick a fight with the world, their country, or even with people. Joni and Susi taught us that a simple love story can be very political." Bila perhatian mendalam kita berikan pada konsep album ini secara komprehensif, kita akan menemukan dua protagonist bernama Joni dan Susi dengan kisah-kisah berdasar rumus Shakespeare: tragic-comedy.
Balada Joni dan Susi mengingatkan saya pada album Ken Arok karya Harry Roesli yang oleh Rolling Stone Indonesia ditempatkan padai posisi 10 dalam 150 Album Terbaik Indonesia. Sama-sama bersifat konsep album dengan dipenuhi karakter bak cerita fiksi. Memang Balada Joni dan Susi belum pernah dioperakan, namun siapa tahu? Mengingat para personil Melancholic Bitch adalah juga pegiat teater di Teater Garasi.
Harry Roesli mementaskan Opera Ken Arok pada tahun 1975, yang dengan cerdas menyindir tradisi suap, korupsi, hipokrisi dalam setting Kerajaan Singosari yang dipimpin Ken Arok setelah merebut kekuasaan Tunggul Ametung secara ilegal (jangan lupa, bahkan merebut istri Tunggul Ametung, Ken Dedes). Pementasan itu dianggap menyajikan konteks dan relevan dengan masyarakat Indonesia yang dipenuhi kegelisahan terhadap lingkungan sosial dan pemerintahannya.
Balada Joni dan Susi juga memiliki konteks dan relevansi dengan zamannya, dengan mitos-nya sendiri. Ini boleh jadi adalah kisah post-modern love story. Mereka bercerita tentang cinta dengan penuh filsafat dan wacana-wacana budaya popular. Terus terngiang-ngiang di benak saya penggalan lirik lagu “Mars Penyembah Berhala”: /Siapa yang membutuhkan imajinasi jika kita sudah punya televisi…/” atau lagu “Akhirnya Masup Tipi”: /Susi aku masup tipi, 15 detik, kerajaanku, lebih baik, jauh lebih baik daripada seumur hidup tanpa lampu. Lihatlah, lihat segalanya nyata di tv, lihat betapa nyata cinta kita kini.../”. Kisah Joni dan Susi yang penuh problematika Rama-Sinta kontemporer di zaman postmodern.
Lirik dalam album ini seperti narasi. Pastinya karena penulis lirik, Ugoran Prasad, juga dikenal sebagai penyair dan penulis. Beberapa karya cerita pendeknya sering menghiasi halaman koran nasional. Maka tak aneh Ugo dengan fasih merajut cerita dari satu lagu ke lagu lainnya. Seperti pada lagu “Intro” yang seolah memperkenalkan sang protagonist: /Ketika Joni dua satu dan Susi Sembilan belas, hidup sedang bergegas di reruntuh ruang kelas. Kota-kota menjalar liar dan rumah terkurung dalam kotak gelas, dingin, dan cemas. Namaku Joni, namamu Susi. Namamu Joni, Namaku Susi/.
Musik Melancholic Bitch dipenuhi nada-nada pop dengan ritmis-ritmis elektronik, sound-sound piano minimalis, dan petikan gitar yang mengingatkan kita pada Jonny Greenwood era OK Computer. Sang vokalis Ugoran justru bisa dibilang bercerita (spoken word) dibandingkan sekedar memamerkan teknik vokal.
Album konsep ini pun bisa jadi tandingan terhadap konsumsi masyarakat Indonesia pada musik. Akhir-akhir ini, telinga kita dimanjakan dengan “hanya” mengonsumsi musik semata. Maka maraklah download rapidshare, limewire, atau RBT. Padahal musik seperti sebuah paket nasi timbel lengkap dengan tambahan menu lirik dan artwork. Mendengarkan album konsep dengan teknik cerita pendek seperti ini tak hanya membuat kita bisa mendengar musiknya semata. Namun, mesti membaca kertas lirik yang ibarat buku cerpen, memejamkan mata meresapi cerita, plus - supaya tambah nikmat-, sambil memakan kudapan kentang goreng.
4. Endah N Rhesa, Nowhere To Go (Demajors Records)
 Sangat menyenangkan menemukan sebuah band yang tidak pretensius dalam berkarya. Dalam Endah N Rhesa saya menemukan kesederhanaan dalam berkarya. Impresi pertama saya terhadap band ini sekitar empat tahun lalu ketika mereka tampil di sebuah Klab Jazz di Bandung. Waktu itu mereka baru saja merilis mini-album Real Life, yang direkam penuh kesederhanaan. Empat lagu yang di rekam secara live low budget tanpa teknik overdub. Kepingan CD-nya pun dibuat CD-R mode atau penggandaan CD lewat burning PC.
Sangat menyenangkan menemukan sebuah band yang tidak pretensius dalam berkarya. Dalam Endah N Rhesa saya menemukan kesederhanaan dalam berkarya. Impresi pertama saya terhadap band ini sekitar empat tahun lalu ketika mereka tampil di sebuah Klab Jazz di Bandung. Waktu itu mereka baru saja merilis mini-album Real Life, yang direkam penuh kesederhanaan. Empat lagu yang di rekam secara live low budget tanpa teknik overdub. Kepingan CD-nya pun dibuat CD-R mode atau penggandaan CD lewat burning PC.Tahun ini mereka baru merilis debut album penuh, setelah puas menjajal Java Jazz dan panggung-panggung jazz lainnya. Secara musikalitas, album Nowhere To Go memang tak memberikan kejutan banyak dan berbeda dibanding EP Real Life- yang dibuat sangat terbatas. Kecuali, kemasan yang lebih baik dan duplikasi lebih banyak.
Endah N Rhesa mencapai popularitasnya lewat album Nowhere To Go. Sekilas memang materi-materi dalam album ini sangat mudah dinikmati, catchy, dan bermain dalam tempo sederhana. Siapapun bisa menikmatinya, tua dan muda. Meskipun sekilas terhitung segmented, namun kualitas musik mereka memiliki range segmen yang lebar. Bisa bermain di pop, folk, jazz, atau blues sekalipun. Bisa menjual juga karena mereka menyanyikan lagu humanis dengan tema cinta dan manusia dibalut musik yang manis.
Ah, cinta adalah tema universal. Silakan, nikmati cinta versi band-band industri yang bertebaran seputar pengkhianatan, selingkuh, atau mencari jodoh. Cinta milik Endah N Rhesa hanya kisah cinta sederhana seperti pada lagu “When You Love Someone”: /When you love someone/just be brave to say/ that you want him to be with you/ when you hold your love/ don’t ever let it go/ or you’ll lose your chance to make your dream come true…/
Kadangkala, para penulis lirik cinta terjebak pada pengumbaran dramatisasi emosi seolah dunia akan runtuh. Atau jika sedang bahagia, cinta seolah membuat dunia milik kita berdua. Namun, lagu-lagu dalam Nowhere To Go sangat layak dijadikan salah satu lagu dalam mixtape jika sedang jatuh cinta. Cinta yang sederhana dan penuh nasihat baik.
Di tengah band-band major asyik menjual cinta-cinta mendayu dan band-band indie sibuk mengkritisi sosial dan budaya popular, Endah N Rhesa adalah anomali.
5. The Trees and The Wild, Rasuk (Lil’Fish Records)
 Terlalu picik rasanya para kritikus musik di manapun jika selalu saja melakukan perbandingan hanya karena memiliki kesamaan berdasar takdir. Misal, membanding-bandingkan musik Interpol dengan Joy Division hanya karena takdir Paul Banks yang memiliki kemiripan suara bariton dengan Ian Curtis. Atau muncul eksponen lainnya macam The Editors, yang digadang mirip Interpol hanya karena warna vokal Tom Smith yang mirip Paul Banks.
Terlalu picik rasanya para kritikus musik di manapun jika selalu saja melakukan perbandingan hanya karena memiliki kesamaan berdasar takdir. Misal, membanding-bandingkan musik Interpol dengan Joy Division hanya karena takdir Paul Banks yang memiliki kemiripan suara bariton dengan Ian Curtis. Atau muncul eksponen lainnya macam The Editors, yang digadang mirip Interpol hanya karena warna vokal Tom Smith yang mirip Paul Banks. Begitu pula yang terjadi pada The Trees and The Wild (TTATW). Entah kenapa banyak orang yang menyamakan suara vokal Remedy Waloni dengan karakter vokal John Mayer, seolah-olah menganggap TTATW hanya sebatas epigon semata. Banyak kritikus di negeri ini terjebak persepsi-persepsi awal para kritikus mulai bekerja. Menikmati sekitar 2-3 lagu di album, pikiran menyebar menebak warna album, dan mulai membanding-bandingkannya dengan warna musik serupa dari para musisi sebelumnya yang telah muncul. Maka tak aneh jika para kritikus atau jurnalis musik selalu memberikan kredit pada sejarah musik.
Mendengarkan musik TTATW justru membuat saya berpikir bahwa band ini memiliki potensi. Meski potensi ini bisa saja dipersempit oleh kredit para kritikus musik lewat perbandingan John Mayer-nya. Ketika saya mendengarkan warna musik TTATW, justru saya pikir jauh dengan musiknya John Mayer. Itu pun jika mendengar sentuhan aransemen, komposisi, dan genre musik, tak hanya dipersepsi lewat vokal saja. TTATW menyuguhkan potensi musik folk dibaur sedikit sentuhan ambience post-rock yang kental. Sehingga sebagian besar lagu-lagu di album ini pun terdengar mengawang, berbeda dengan kebanyakan band folk yang lebih groovy.
Warna kentara yang menyegarkan dalam musik TTATW ada pada lagu “Verdure”. Sentuhan melodi panjang menghentak ditimpali crescendo ala post-rock sebelum bergumul menjadi alunan vokal yang datar dan menghanyutkan. Ya, saya pikir terminologi tepat untuk musiknya TTATW adalah: menghanyutkan.
Formula-formula menghanyutkan yang sama bisa kita temukan dalam TTATW. Single pertama “Honeymoon On Ice” yang terinspirasi dari film Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, adalah contoh besarnya. Atau repetisi yang sama pada lagu-lagu seperti “Malino”, yang lebih terdengar lebih seperti Sigur Ros. Atau lagu “Our Roots” yang berisi ambience dengan gaya vokal mengawang seperti tipikalisasi band-band Islandia sebagai salah satu pengaruh kuat dalam musik TTATW.
Salah satu lagu favorit saya, “Derau dan Kesalahan” adalah pameran terbaik kualitas potensi band asal Jakarta ini. Mereka memamerkan melodi yang indah sebelum ditutup hentakan gitar crescendo seperti Jonny Greenwood melakukannya pada Radiohead.